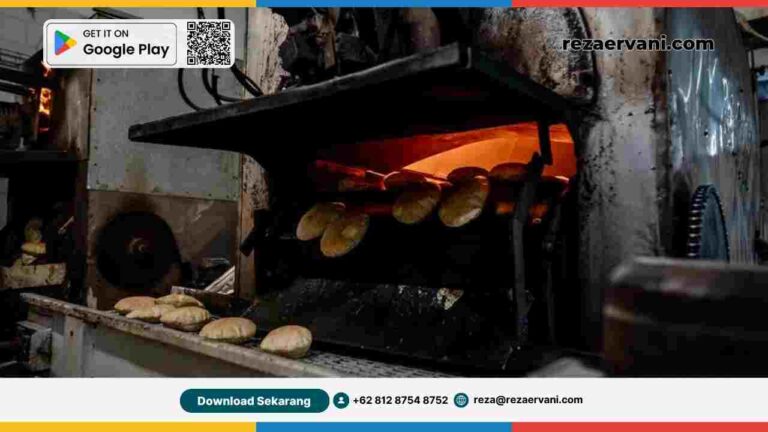Pelajar Gaza 2023 Ikuti Ujian di Tengah Perang
rezaervani.com – 27 September 2025 – Setelah dua tahun perang dan penundaan, ribuan Pelajar Gaza 2023 akhirnya mengikuti ujian akhir ditengah lapar, trauma, dan penjajahan untuk mengikuti ujian akhir sekolah menengah.
Pada pagi hari ujian terakhirnya, Tawfiq Abu Dallal mendapat telepon dari seorang teman. Kakak dan sepupunya baru saja terluka dalam serangan udara Israel saat menjenguk bibinya di lingkungan al-Zeitoun, Kota Gaza.
Abu Dallal berlari sejauh 3 km ke rumah sakit, melihat mereka masih hidup, lalu buru-buru kembali ke ruang ujian – terlambat 30 menit.
“Aku tidak bisa fokus pada jawabanku,” kata remaja Palestina itu kepada Middle East Eye. “Aku hanya ingin segera selesai dan kembali pada mereka.”
Abu Dallal adalah salah satu dari ribuan siswa di Gaza yang mengikuti ujian sekolah menengah awal bulan ini, hampir dua tahun setelah angkatan 2023 di seluruh dunia sudah masuk universitas.
Penundaan itu terjadi di tengah genosida Israel yang sedang berlangsung di Gaza, dengan Kementerian Pendidikan menunda ujian dua kali sebelum akhirnya mengumumkan ujian akan digelar secara daring melalui aplikasi WiseSchool pada 6 September, di puncak serangan Israel untuk menduduki Jalur Gaza.
Meski invasi darat semakin meluas, kementerian tetap pada jadwal, sambil menjanjikan kelonggaran bagi yang tidak bisa hadir.
Bagi Abu Dallal yang berusia 19 tahun dari lingkungan al-Sabra, persiapan ujian berarti bertahan hidup di tengah pemboman harian, kelaparan, dan pengungsian berulang.

Dengan pusat internet hancur, ia sering berjalan 2 km ke pusat pendidikan untuk mengakses data eSIM.
Anak sulung dari enam bersaudara ini sejak lama bermimpi menjadi jurnalis untuk menghidupi keluarganya. Namun sejak perang dimulai 7 Oktober 2023, pendidikannya terpotong menjadi momen singkat di antara mengumpulkan kayu bakar, mengambil air, antre bantuan, dan membantu adik-adiknya mengungsi di bawah tembakan.
“Adik-adikku terlalu kecil untuk mengangkat barang berat, jadi aku harus membantu mereka,” katanya.
“Kadang-kadang tank Israel mengebom beberapa kilometer jauhnya. Aku tidak yakin bisa hidup cukup lama untuk lulus, tapi aku terus belajar.”
Keluarganya mengorbankan apa pun yang tersisa. Ibunya memberinya porsi makanan terbesar. Ayahnya membongkar perabotan untuk dijual sebagai kayu bakar, lalu uangnya dipakai membeli buku dan kopi untuknya. Neneknya, Sameha (72), menyimpan permen dan tepung putih hanya untuknya.
Setelah rumah mereka di Shujaiya dibom, Sameha dan empat putranya mengungsi ke Sekolah al-Majdal. Tawfiq bergabung sebulan lalu setelah serangan udara menghantam dekat rumahnya.
“Dia duduk di pintu kelas, mencegah pamanku masuk agar aku bisa belajar,” kenangnya.
“Dia selalu bilang menunggu hari aku merayakan kelulusan.”
Pada 12 Agustus, serangan udara Israel menghantam dekat sekolah. Pecahan peluru mengenai leher Sameha dan membunuhnya.
“Aku berada di dekatnya. Kata-kata terakhirnya adalah meminta pamanku menjaga diriku,” kata Abu Dallal dengan mata berkaca-kaca.
“Kehilangannya menghancurkan hatiku. Aku tidak bisa belajar selama dua minggu. Lalu aku memutuskan untuk bertahan – demi dia.”
Setelah kematiannya, paman-pamannya beserta keluarga mereka kembali tinggal bersama keluarganya – 35 orang di bawah satu atap.
“Aku belajar larut malam dengan cahaya senter ponsel, di tengah pemboman Israel dan robot penuh bahan peledak,” kenangnya.
Belajar di Tengah Serangan Panik
Bagi Malak al-Qishawi (19), setiap perjalanan untuk belajar atau ujian terasa seperti salam perpisahan terakhir dengan keluarganya.
Sebelum pergi, orang tuanya selalu memberi instruksi bertahan hidup:
Ubah rute jika jalanan kosong. Selalu tanyakan pada orang apakah aman untuk melanjutkan. Hubungi saat tiba di titik penting. Tiarap jika ada bangunan di dekatmu yang dibom. Jika tiba-tiba dikepung pasukan darat, tetap di tempat dan tidur di sana.
Kadang-kadang, orang tuanya bahkan menemaninya berjalan.
Ketakutannya makin menjadi beberapa hari sebelum ujian, ketika temannya Haneen terbunuh saat berjalan menuju tempat internet.
“Aku membayangkan itu bisa saja aku,” katanya.
Keesokan harinya, ibu dan kakaknya menemaninya ke ruang ujian. Dalam perjalanan pulang, tiga serangan udara Israel menghantam gedung di depan mereka.
“Kami bergegas masuk ke rumah orang asing dan tinggal di sana selama satu jam. Aku mengalami serangan panik. Saat akhirnya keluar, kami berlari pulang menempel ke dinding jalan,” kenangnya.
Hari berikutnya ia hanya berbaring di tempat tidur, sakit dan lelah. Namun ia bangun keesokan paginya, tepat waktu untuk ujian berikutnya.
“Selama beberapa minggu terakhir, aku mengikuti semua ujian dengan hanya beberapa jam belajar. Situasi di Kota Gaza benar-benar mengerikan.”
Keluarganya menolak mengungsi ke selatan, tapi terpaksa berpindah berulang kali antar tempat penampungan sementara di Kota Gaza.
Ia pernah berharap bisa fokus belajar setelah perang berakhir, namun dukungan keluarganya, terutama Abdulrahman (20), kakaknya, yang memberinya kekuatan untuk bertahan.
Pada Juli 2024, ketika mereka mulai menetap di apartemen sementara di Jalan al-Jala, serangan udara Israel menghantam lantai atas. Empat orang tewas, termasuk Abdulrahman yang terkena pecahan peluru di kepala dan meninggal seketika.
“Aku tidak bisa belajar berbulan-bulan setelah kematiannya,” kata Qishawi. “Tapi aku ingin membawa sedikit kebahagiaan kembali ke keluarga lewat kesuksesanku di masa depan.”
Qishawi berharap bisa belajar arsitektur setelah perang dan bekerja daring – meyakini pekerjaan jarak jauh lebih aman di Gaza, di mana kantor-kantor sering dihancurkan dalam eskalasi Israel – meski pemadaman internet meluas.
“Banyak orang di dunia mengira kami hanya butuh beasiswa untuk belajar,” katanya.
“Tapi mereka tidak menyadari bahwa banyak siswa tidak bisa meninggalkan keluarganya saat mereka menderita.
“Sebagai seorang gadis muda, pelajar, dan warga Gaza, yang kuinginkan hanyalah perang ini segera berakhir.”
Belajar di Tenda
Di lingkungan al-Sabra, Gaza City, Aya Draimli (18) merasa sangat gembira akhirnya menyelesaikan ujian sekolah menengah setelah dua tahun terganggu perang.
Sering menjadi peringkat pertama di kelasnya, Draimli berjuang keras untuk tetap belajar, mempertahankan mimpinya menjadi dokter. Tapi jalannya jauh dari mudah.
Pada November 2023, saat invasi darat pertama Israel ke Kota Gaza, Draimli dan keluarganya yang berjumlah lima orang mengungsi ke selatan tanpa membawa apa pun – tanpa pakaian, buku, atau barang-barang lain – hingga akhirnya tinggal di tenda darurat di jalanan al-Zawaida.
“Aku berharap perang segera berakhir,” katanya. “Tapi setelah tiga bulan, aku memutuskan kembali belajar.”
Tidak mampu membeli buku baru, ia meminjam dari teman dan mencatat pelajaran di ponselnya.
“Kadang aku membuat ringkasan agar bisa membacanya kembali nanti,” katanya.
Sumber : Middle East Eye