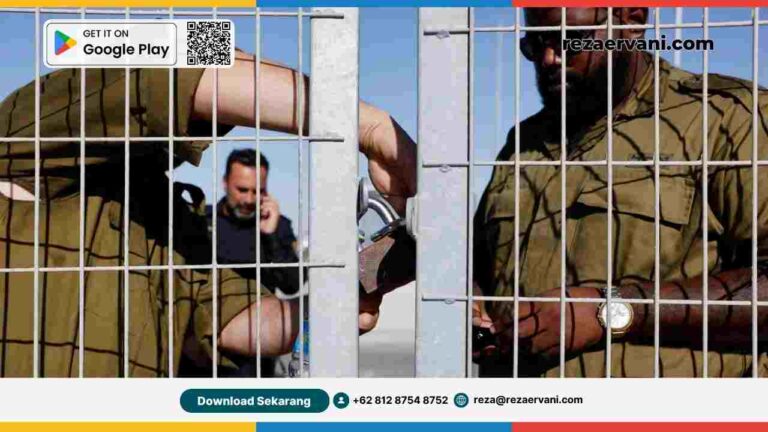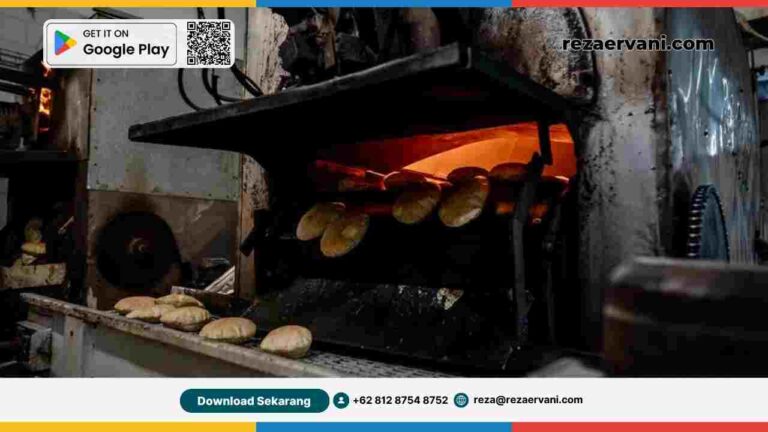Perang di Gaza dan Bangkitnya Kembali Imperialisme (Bagian Pertama)
Oleh : Hisyam Ja’far (al Jazeera)
Artikel Perang di Gaza dan Bangkitnya Kembali Imperialisme ini masuk dalam Kategori Analisa
Istilah imperialisme dulunya sering muncul dalam masa perjuangan kemerdekaan dan penolakan terhadap penjajahan. Hingga kini, kelompok kiri radikal masih menggunakannya. Tapi dalam wacana politik Arab saat ini, kata imperialisme sudah jarang terdengar. Karena itu, penting untuk kembali mengingatkan makna istilah ini kepada para pembaca.
Imperialisme adalah kebijakan suatu negara untuk memperluas kendali atas negara dan rakyat lain, demi memperbesar pengaruhnya dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan budaya.
Secara historis, imperialisme berkaitan dengan kemunculan negara-negara bangsa di Eropa dan persaingan antar mereka. Namun, yang kita lihat selama satu dekade terakhir adalah bentuk baru dari persaingan ekonomi dan geopolitik (terkadang juga kerja sama), yang kini terjadi antara apa yang disebut sebagai negara peradaban, bukan lagi antar negara bangsa seperti sebelumnya.
Menariknya, bentuk imperialisme saat ini justru kembali ke model awalnya: penaklukan langsung, pendudukan wilayah, serta pengusiran atau pemindahan penduduk. Ini terlihat di Ukraina, dan juga dalam rencana Trump untuk mencaplok Panama dan Greenland. Sementara di Gaza, tujuannya bukan untuk mengintegrasikannya ke dalam wilayah Israel atau membangun kembali pemukiman Yahudi, tapi untuk mengusir penduduknya dan menguasai lahannya melalui proyek-proyek properti.
Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan negara peradaban, yang kini mulai menggantikan konsep negara bangsa yang sudah dikenal sejak Perjanjian Westphalia tahun 1648? Dan bagaimana posisi perang di Gaza dalam pergeseran besar arah konflik global ini?
Serangan Negara Peradaban
Menurut saya, negara peradaban punya empat ciri utama yang membedakannya dari negara bangsa—seperti yang dikenal sejak sistem Westphalia tahun 1648.
1. Melampaui Batas Negara Bangsa
Negara bangsa memisahkan antara budaya dan politik, serta memisahkan nilai dari kepentingan. Negara bangsa membentuk identitas baru berdasarkan kewarganegaraan. Dalam sistem ini, perbedaan dan konflik biasanya muncul dari perbedaan pandangan politik atau kepentingan nasional, bukan karena perbedaan agama atau budaya.
Sementara itu, konsep negara peradaban didasarkan pada keyakinan—seperti yang dijelaskan oleh Massis, mantan Menteri Urusan Eropa dari Portugal—bahwa negara bangsa adalah ciptaan Barat, dan karena itu mudah dipengaruhi oleh Barat. Sebaliknya, peradaban dianggap sebagai alternatif dari dominasi Barat.
Contohnya, pemerintahan Narendra Modi di India sering menyebut India sebagai sebuah peradaban, bukan hanya negara biasa. Dengan cara ini, lawan politik seperti Partai Kongres digambarkan seolah mewakili pengaruh Barat karena mereka menggunakan standar asing untuk menilai kemajuan India.
Nilai-nilai seperti sekularisme (pemisahan agama dan negara) dan internasionalisme, yang dulu jadi ciri khas Partai Kongres, sekarang dianggap sebagai warisan budaya asing yang tak cocok lagi dengan jati diri India.
Hal serupa juga tampak di Turki. Kebijakan politik dan militernya di Kaukasus Selatan dan Timur Tengah dilihat sebagai bentuk kebangkitan kejayaan Turki. Presiden Erdoğan berkali-kali menegaskan bahwa Turki akan hadir di tempat-tempat yang ia anggap sebagai bagian dari peradaban Turki.
2. Menolak Nilai-Nilai Universal
Setelah Perang Dunia Kedua, dunia banyak dipengaruhi oleh sistem liberal Barat yang menekankan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia dan kebebasan individu. Tapi bagi negara peradaban, nilai-nilai tersebut dianggap tidak cocok untuk semua. Mereka percaya bahwa setiap negara punya nilai dan tradisi sendiri, sehingga tidak ada satu sistem yang bisa dipaksakan untuk seluruh dunia.
Hal ini terlihat jelas di Rusia di bawah Vladimir Putin dan di Tiongkok di bawah Xi Jinping. Keduanya menolak mengikuti aturan dan nilai-nilai dari sistem liberal Barat. Penolakan ini juga mendorong negara-negara Barat mulai memandang diri mereka bukan hanya sebagai negara bangsa, tetapi juga sebagai peradaban yang unik.
Putin, misalnya, mengajak rakyat Rusia untuk menolak gaya hidup Barat yang menekankan kebebasan pribadi. Ia mengajak mereka membangun kembali kejayaan Rusia bersama-sama.
Presiden Tiongkok pun menyuarakan hal serupa saat membahas proyek besar Tiongkok untuk kebangkitan nasional. Ia menegaskan bahwa budaya Tiongkok memiliki kekhasan yang berbeda dari budaya individualis ala Barat. Sementara Presiden Turki menolak nilai-nilai Barat dalam isu-isu seperti peran perempuan, dan lebih mendukung konsep keluarga tradisional.
Dulu, sebagian pihak menggambarkan perang melawan terorisme—yang dimulai tahun 2001 dan banyak terjadi di dunia Islam atau Timur Tengah Raya—sebagai perang peradaban antara Barat dan Islam. Namun anggapan itu kemudian ditinggalkan. Perang ini akhirnya dijelaskan sebagai upaya menyebarkan nilai-nilai demokrasi.
George W. Bush berulang kali menyatakan bahwa perang global melawan terorisme dan pergantian rezim di Irak dilakukan demi menciptakan dunia baru yang mengikuti sistem liberal, bukan atas dasar teori benturan peradaban seperti yang dikemukakan Samuel Huntington.
Bush (yang menjabat dari 2001 hingga 2009) pernah berkata :
“Kalau soal hak dan kebutuhan dasar laki-laki dan perempuan, tidak ada benturan antar peradaban.”
Ia juga menambahkan, “Tuntutan akan kebebasan juga berlaku penuh di Afrika, Amerika Latin, dan seluruh dunia Islam. Masyarakat di negara-negara Islam ingin dan layak menikmati kebebasan serta kesempatan yang sama seperti masyarakat di negara lain. Pemerintah mereka harus mendengarkan harapan rakyatnya.”
Meski perang melawan teror mengandung unsur budaya, intinya adalah perebutan kekuasaan antar negara besar, di mana kepentingan geopolitik dan nilai budaya saling bercampur. Ini menjadi ajang persaingan kekuatan dunia dalam tatanan global yang terus berubah.
Sejak peristiwa 11 September, Amerika Serikat menggunakan kekuatannya untuk melonggarkan batas penggunaan kekuatan militer. Setelah tahun 2001, perang terhadap terorisme mengurangi peran aturan internasional. AS menggunakan dominasinya untuk memaksa, membujuk, atau merayu negara-negara lain agar ikut serta dalam aksi militer, tanpa terlalu memikirkan dampak jangka panjang terhadap hubungan dengan dunia non-Barat.
Sejak krisis keuangan global tahun 2009—paling tidak sejak saat itu—negara-negara kekuatan baru di kawasan Selatan Global mulai lebih berani menyuarakan ketidakpuasan mereka. Mereka menilai bahwa “sistem berbasis aturan internasional hanyalah omong kosong.”
Negara-negara ini semakin terang-terangan menunjukkan kekecewaan mereka terhadap kemunafikan yang ada dalam sistem global saat ini.
Narasi anti-Barat yang dibawa Rusia dan Tiongkok memang tidak menciptakan kemarahan ini dari awal, tapi mereka menyediakan bahasa dan cara bicara bagi negara-negara Selatan Global untuk menyampaikan perasaan mereka yang selama ini terpendam: bahwa sistem global yang katanya “berbasis aturan” itu sebenarnya hanya kedok moral untuk menjaga kekuasaan, dominasi, dan kepentingan negara-negara Barat.
Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah